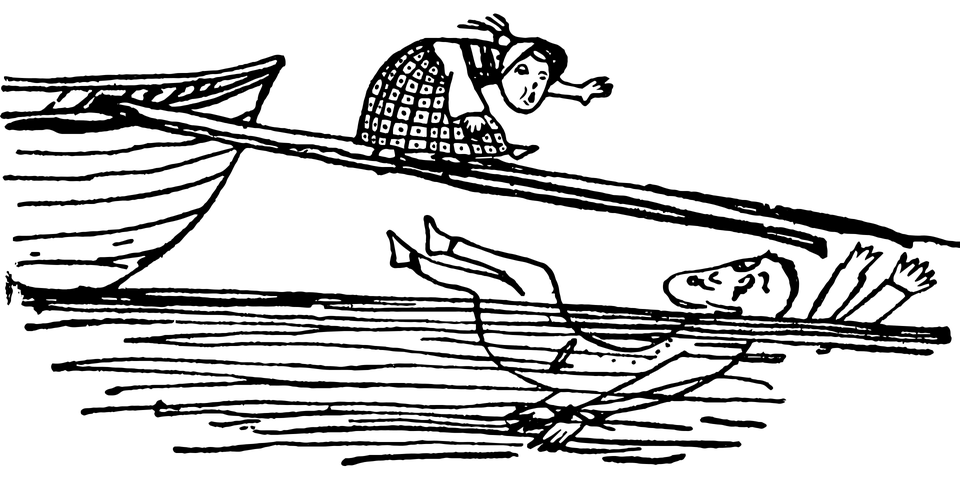“Pembatasan makna agama tersebut seringkali berakibat menafikkan agama diluar agama arus utama (mainstream), misalnya pengikut agama leluhur,”

Serat.id – Guru Besar Riset lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Ahmad Najib Burhani menyebut kedekatan politik agama dan negara sering menyebabkan tekanan bagi agama minoritas atau penghayat kepercayaan. Hasilnya kelompok penghayat sering menjadi korban regulasi yang diskriminatif.
“Pembatasan makna agama tersebut seringkali berakibat menafikkan agama diluar agama arus utama (mainstream), misalnya pengikut agama leluhur,” ujar Najib saat webinar Keragaman Agama dan Tatakelolanya di Ruang Publik Pasca-Reformasi, Selasa, 11 Mei 2021.
Baca juga : Sujudan Kecepit Ritual Penghayat Kepercayaan Perguruan Trijaya
Sambut 1 Suro, Warga Gelar Doa Bersama hingga Parade Tumpeng
Tokoh Lintas Agama Segera mengajukan Judisial Review Omnibus Law
Sebaliknya Najib menyatakan ketika kedekatan antara politik agama dan negara telah merenggang, kelompok minoritas agama atau penghayat kepercayaann lebih merasa dihargai haknya. Penjelasan itu mengacu pada sejarah bangsa Indonesia, setidaknya terdapat tiga fase penting pasang surut antara hubungan politik agama dan negara berdampak langsung pada penghayat kepercayaan.
Fase pertama adalah pada tahun 1965 pada masa akhir periode kekuasaan Presiden Soekarno dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Imbas aturan ini penghayat kepercayaan tak hanya dipandang sebagai ancaman terhadap agama, namun dilihat sebagai tindakan penodaan agama dan memecah belah persatuan nasional.
“Para pengikut kepercayaan dianggap sebagai orang yang tak beragama atau belum beragama, bahkan mereka dianggap memiliki keyakinan tidak sehat, karena itu harus dibina dan diarahkan kepada keyakinan yang benar,” ujar Najib menjelaskan.
Nasib mereka diperparah pasca perisitwa G 30 September. Mereka yang dikategorikan sebagai kelompok abangan dianggap sebagai golongan komunis. Mereka kemudian menjadi korban dan terpaksa memeluk salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah. Kondisi itu saat jumlah penghayat kepercayaan mengalami penurunan yang signifikan.
Fase suram yang kedua yakni pada masa Orde Baru ketika dikeluarkannya TAP MPR nomorIV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mengelompokkan aliran kepercayaan bukan sebagai kelompok penghayat kepercayaan. Padahal sebelumnya TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN mengategorikan aliran agama dan kepercayaan dianggap setara.
Sedangkan fase ketiga ialah fase surutnya politk agama dan negara pada tahun 2017 ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan di Indonesia, terkait Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UU No. 24 tahun 2013) dengan keluarnya putusan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Imbas putusan ini maka penghayat kepercayaan dapat dimasukkan identitasnya dalam KTP elektronik.
“Pada praktiknya penghayat kepercayaan tidak dimasukkan dalam kolom agama. Justru kolom agama diganti dengan kolom kepercayaan,” ujar Najib menambahkan. Menurut Najib penghayat kepercayaan di Indonesia telah